Menu Kategori
- Home
- Peristiwa
- Perang
- Narkoba
- Politik
- Bisnis
- Tekno
- Medis
- Olahraga
- Sepakbola
- MotoGP
- Sorot
- Film
- Musik
- Seleb
- Royal
- Liburan
- Destinasi
- Kuliner
- Opini
- Style
- Analisis
- Lingkungan
- Nusantara

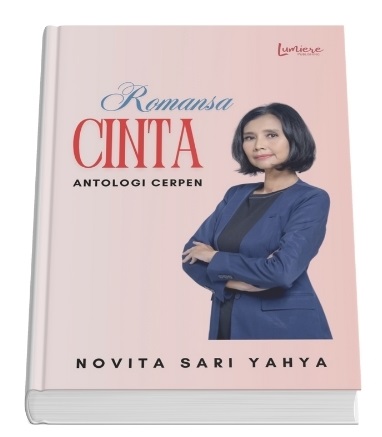
Pendahuluan
Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena perceraian di kalangan selebritas dan publik figur di Indonesia telah menjadi perhatian publik dan media massa. Pemberitaan tentang kehidupan pribadi selebritas mendominasi tayangan televisi dan media sosial, terutama dalam format acara gosip yang disiarkan dari pagi hingga malam hari. Fenomena ini menunjukkan bagaimana media berperan bukan hanya sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan opini sosial dan reproduksi nilai-nilai budaya, khususnya dalam konteks relasi gender.
Kebiasaan menonton acara gosip dan mengonsumsi berita perceraian selebritas telah menjadi bagian dari aktivitas sosial masyarakat, terutama di kalangan perempuan. Setelah menyelesaikan pekerjaan domestik, banyak perempuan menggunakan waktu luang untuk menonton acara gosip atau mengakses media sosial seperti Instagram dan TikTok, di mana kisah perceraian selebritas diangkat sebagai konten yang menarik perhatian publik. Aktivitas ini berlanjut dalam interaksi sosial sehari-hari, seperti pertemuan sore atau obrolan santai di lingkungan sekitar, di mana topik-topik tersebut dibahas secara terbuka.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa kisah perceraian selebritas bukan hanya hiburan, melainkan juga cermin sosial yang mencerminkan nilai-nilai budaya, norma gender, dan struktur relasi kuasa dalam masyarakat Indonesia kontemporer.
Fenomena Media dan Representasi Gender
Dominasi isu perceraian selebritas di media menggambarkan adanya pola konsumsi informasi yang berbasis drama emosional. Media membungkus kenyataan personal menjadi narasi publik yang berorientasi pada sensasi. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan pribadi selebritas diperlakukan sebagai “komoditas simbolik” yang memiliki nilai jual tinggi, sekaligus ruang bagi masyarakat untuk melakukan proyeksi sosial atas kehidupan mereka sendiri (Heryanto, 2014).
Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa media tidak netral dalam membingkai isu-isu gender. Perempuan selebritas sering kali digambarkan dalam posisi emosional dan rentan, sedangkan laki-laki ditampilkan sebagai figur rasional dan dominan. Dengan demikian, media turut memperkuat stereotip gender tradisional, di mana perempuan diposisikan sebagai pihak yang tunduk dan laki-laki sebagai pihak yang berkuasa.
Maskulinitas Hegemonik dan Ketimpangan Relasi
Dalam perspektif psikologi sosial dan sosiologi gender, ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan melalui konsep maskulinitas hegemonik (Connell, 2005). Maskulinitas hegemonik merujuk pada struktur sosial dan kultural yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan simbolik dan praktis dalam masyarakat. Konsep ini menjelaskan bagaimana norma-norma gender membentuk perilaku, identitas, dan ekspektasi sosial terhadap peran laki-laki dan perempuan.
Menurut Connell dan Messerschmidt (2005), maskulinitas hegemonik bukanlah bentuk maskulinitas tunggal, melainkan posisi dominan dalam hierarki sosial yang terus berubah sesuai konteks budaya dan sejarah. Ia tidak selalu diwujudkan melalui kekerasan fisik, melainkan juga lewat mekanisme simbolik, budaya, dan institusional yang menormalisasi dominasi laki-laki dalam tatanan sosial.
Maskulinitas hegemonik berkontribusi terhadap pelestarian ketimpangan gender melalui beberapa mekanisme utama, yaitu:
1. Subordinasi perempuan, yang menempatkan perempuan dalam posisi sosial yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, baik dalam ruang domestik maupun publik. Hal ini tampak dalam pembagian kerja berbasis gender, ekspektasi peran keluarga, serta representasi perempuan di media.
2. Hierarki antarlaki-laki, di mana hanya bentuk maskulinitas yang dominan dan sesuai standar sosial yang mendapat penghargaan. Sementara itu, ekspresi maskulinitas lain yang dianggap lemah atau berbeda (misalnya laki-laki yang sensitif, emosional, atau tidak sesuai norma heteronormatif) mengalami marginalisasi.
3. Tindakan dominasi kultural, di mana kekuasaan laki-laki dilegitimasi melalui sistem sosial dan bahasa yang meneguhkan nilai “rasionalitas”, “kekuatan”, dan “kewibawaan” sebagai identitas maskulin ideal.
4. Penindasan emosional, yaitu penanaman nilai bahwa laki-laki harus kuat, rasional, dan tidak mengekspresikan emosi. Akibatnya, muncul jarak emosional dalam hubungan interpersonal serta krisis identitas ketika ekspektasi sosial tidak terpenuhi.
Selain itu, Connell (1995) menjelaskan adanya beragam tipe maskulinitas yang berinteraksi dalam sistem patriarki: Maskulinitas hegemonik, yaitu bentuk dominan yang menjustifikasi struktur patriarki dan meneguhkan kontrol laki-laki atas perempuan serta atas laki-laki lain. Maskulinitas komplit (complicit masculinity), yakni laki-laki yang tidak sepenuhnya menjalankan praktik hegemonik, tetapi tetap memperoleh keuntungan sosial dari sistem patriarki. Maskulinitas subordinat (subordinated masculinity), yaitu laki-laki yang berada dalam posisi sosial inferior terhadap maskulinitas dominan, seperti laki-laki gay. Maskulinitas termarjinalkan (marginalized masculinity), yaitu bentuk maskulinitas yang dilemahkan karena faktor kelas, ras, atau etnisitas, meskipun individu tersebut tetap mungkin mengadopsi nilai-nilai patriarki.
Dengan demikian, konsep maskulinitas hegemonik bersifat dinamis dan kontekstual, bergantung pada perubahan sosial, budaya, dan politik. Dalam masyarakat modern, wacana tentang kesetaraan gender dan feminisme mulai menantang posisi hegemonik ini, sekaligus membuka ruang bagi munculnya maskulinitas baru yang lebih inklusif dan egaliter.
Media, Sosialisasi, dan Reproduksi Norma Gender
Media massa, baik televisi maupun media sosial, memiliki peran sentral dalam mereproduksi dan melegitimasi norma-norma gender. Tayangan gosip dan konten perceraian selebritas tidak hanya menjadi sumber hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai sosial tentang relasi, kekuasaan, dan gender.
Dalam konteks ini, maskulinitas hegemonik direpresentasikan melalui narasi tentang laki-laki yang rasional, tegas, dan berwibawa, sementara perempuan digambarkan sebagai emosional dan impulsif. Representasi semacam ini memperkuat pandangan bahwa laki-laki memiliki kontrol sosial dan moral yang lebih besar dalam relasi, sementara perempuan diposisikan sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri.
Dengan demikian, drama perceraian selebritas yang disajikan dalam media sesungguhnya merupakan refleksi dari dinamika relasi kuasa patriarki yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia. Meskipun dikemas sebagai hiburan, narasi tersebut memiliki fungsi ideologis yang memperkuat tatanan sosial yang tidak setara.
Kesimpulan
Fenomena perceraian selebritas di Indonesia bukan sekadar bentuk hiburan populer, melainkan juga manifestasi dari struktur sosial dan budaya yang lebih dalam. Melalui media, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga peserta dalam reproduksi nilai-nilai gender yang hierarkis.
Konsep maskulinitas hegemonik memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami bagaimana norma gender diinternalisasi dan dipertahankan melalui mekanisme sosial dan simbolik, termasuk media. Dengan memahami hal ini, analisis psikologi sosial dapat berperan dalam membuka kesadaran kritis masyarakat terhadap ketimpangan relasi yang sering kali tersembunyi di balik narasi hiburan dan gosip publik.
Daftar Referensi
Connell, R. W. (1995). Masculinities. Berkeley: University of California Press.
Connell, R. W. (2005). Masculinities (2nd ed.). Berkeley: University of California Press.
Connell, R. W., & Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic masculinity: Rethinking the concept. Gender & Society, 19(6), 829–859.
Hearn, J. (2004). From hegemonic masculinity to the hegemony of men. Feminist Theory, 5(1), 49–72.
Hooks, bell. (2000). Feminism is for Everybody: Passionate Politics. South End Press.
Kimmel, M. (2017). The Gendered Society (6th ed.). New York: Oxford University Press.
Mulvey, L. (1999). Visual pleasure and narrative cinema. In Film Theory and Criticism (pp. 833–844). Oxford University Press.
Schippers, M. (2007). Recovering the feminine other: Masculinity, femininity, and gender hegemony. Theory and Society, 36(1), 85–102.
Wood, J. T. (2015). Gendered Lives: Communication, Gender, and Culture. Boston: Cengage Learning.
Heryanto, A. (2014). Identity and Pleasure: The Politics of Indonesian Screen Culture. Singapore: NUS Press.
*Penulis adalah Seorang Peneliti dan Penulis Buku Romansa Cinta
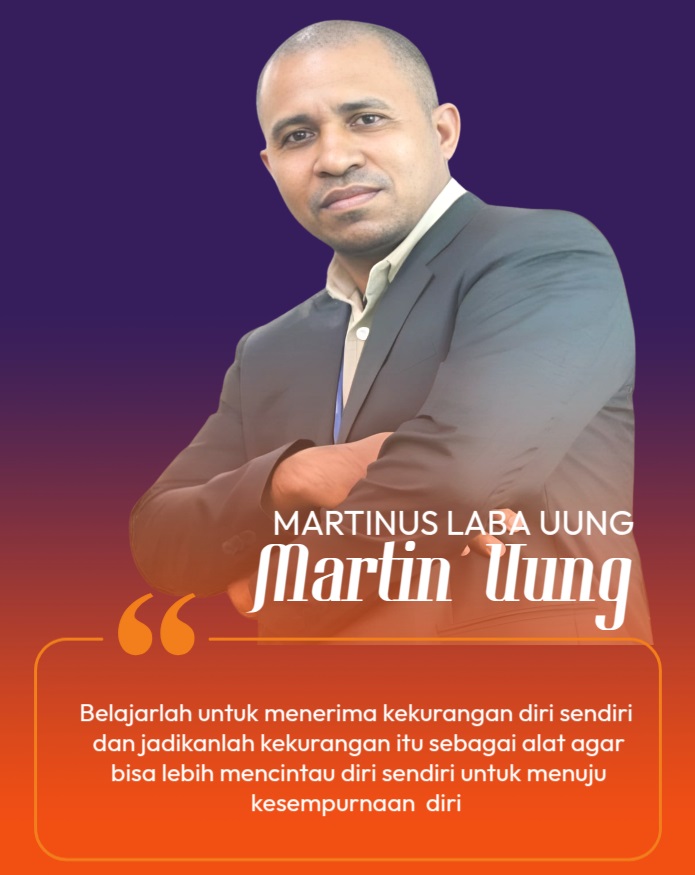

2.65K
141