Menu Kategori
- Home
- Peristiwa
- Perang
- Narkoba
- Politik
- Bisnis
- Tekno
- Medis
- Olahraga
- Sepakbola
- MotoGP
- Sorot
- Film
- Musik
- Seleb
- Royal
- Liburan
- Destinasi
- Kuliner
- Opini
- Style
- Analisis
- Lingkungan
- Nusantara


“Dangakan nan diurang, laluan nan diawak.”
“Lamak dek awak, katuju dek urang.”
Dua ungkapan lama Minangkabau ini mungkin sederhana di telinga, namun mengandung falsafah mendalam tentang cara pandang orang Minang menghadapi dunia luar. Keduanya menandai sikap unik mendengar tanpa kehilangan pendirian, berbuat untuk diri sendiri tanpa menyakiti orang lain. Sikap inilah yang menjadi penopang lahirnya generasi intelektual Minang di masa kolonial Belanda generasi yang kelak mengguncang tatanan kekuasaan kolonial dan menjadi lokomotif lahirnya Republik Indonesia.
Kesempatan dari Kolonialisme
Pada paruh akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, kebijakan politik etis dan perluasan pendidikan Barat membuka jalan bagi sejumlah pemuda dari keluarga terkemuka di Minangkabau untuk menempuh pendidikan modern, bahkan sampai ke negeri Belanda. Bagi pemerintah kolonial, langkah ini diyakini sebagai strategi “penghalusan” bumiputera dengan harapan kaum terdidik akan menjadi jembatan penghubung antara penguasa dan rakyat, sekaligus memperkuat loyalitas pada Hindia Belanda.
Namun apa yang terjadi berbeda dari yang diduga. Generasi muda Minang memanfaatkan pendidikan Barat bukan untuk mengabdi semata, melainkan untuk memahami dan kemudian melawan. Mereka belajar filsafat, ekonomi, hukum, dan politik Barat untuk membongkar logika kolonial dan merumuskan strategi pembebasan. Dari rahim tradisi Minangkabau yang egaliter lahirlah tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Sutan Sjahrir, Mohammad Hatta, M.Yamin dan Tan Malaka nama-nama yang kelak menorehkan sejarah panjang pergerakan nasional.
Budaya Egaliter dan Nalar Kritis
Keunikan Minangkabau terletak pada budaya egaliter yang jarang ditemui di masyarakat feodal Nusantara. Sistem matrilineal di mana garis keturunan mengikuti ibu membuat kepemimpinan tidak terpusat pada satu figur patriarkal. Forum musyawarah nagari, tradisi lapau sebagai ruang diskusi, serta surau sebagai pusat pendidikan agama membentuk karakter masyarakat yang berani berpendapat dan terbuka terhadap perbedaan.
Ungkapan Minang lain berbunyi, “Di kandang kambing mamembek, di kandang harimau mangaum.” Ini bukan soal menjadi kambing atau harimau secara harfiah, melainkan kemampuan menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri. Ketika berada di lingkungan asing, orang Minang mampu mengikuti alur, namun tetap menyimpan sikap kritis terhadap keadaan.
Antropolog Clifford Geertz, dalam konsepnya tentang "thick description ", menekankan bahwa pemahaman budaya memerlukan pembacaan yang mendalam dan kontekstual. Dalam kerangka ini, budaya Minang dapat dipahami sebagai sistem makna yang kokoh mampu menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan identitasnya.
“Budaya yang kuat tidak pernah sekadar menjadi korban perubahan ia memilih, menyaring, dan menegosiasikan apa yang berguna bagi kelangsungan dirinya.” Pandangan ini sejalan dengan realitas Minangkabau yang merantau luas namun tetap pulang dengan jiwa Minang.
Moderasi Bukan Plin-plan
Sebagian pihak kadang menganggap sikap moderat orang Minang sebagai bentuk inkonsistensi. Tuduhan ini lahir karena mereka sering tampak akrab dengan dunia Barat, tetapi sekaligus menjadi penggerak perlawanan terhadap kolonialisme. Namun dalam perspektif budaya Minang, moderasi adalah strategi tidak tunduk membabi buta, namun juga tidak melawan tanpa perhitungan.
Sikap ini terlihat jelas pada pemuda-pemuda Minang era kolonial. Mereka menempuh pendidikan di sekolah Belanda, menguasai bahasa dan cara berpikir Barat, tetapi bukan untuk menjadi “priyayi kolonial.” Pendidikan dijadikan alat untuk memahami musuh sekaligus senjata untuk membangun kekuatan bangsa sendiri.
Merantau sebagai Modal Intelektual
Tradisi merantau adalah napas panjang kebudayaan Minang. Sejak lama, pemuda Minang terbiasa meninggalkan kampung halaman untuk mencari pengalaman, ilmu, dan penghidupan. Merantau bukan sekadar soal ekonomi, tetapi proses pendewasaan sosial dan intelektual.
Ketika kolonial Belanda membuka sekolah-sekolah modern, mental perantau ini membuat pemuda Minang cepat beradaptasi. Mereka melihat peluang, bukan ancaman. Mereka sadar, memahami cara berpikir Barat adalah jalan untuk memajukan kampung halaman. Falsafah “lamak di awak, katuju di urang” pun menjelma strategi kultural mengambil manfaat dari dunia luar tanpa kehilangan tujuan mulia untuk bangsanya sendiri.
Membaca SWOT Sejarah Minang
Jika menggunakan kacamata analisis modern seperti SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), strategi generasi Minang masa kolonial begitu jelas:
Kekuatan (Strengths): budaya egaliter, tradisi intelektual surau, jaringan diaspora yang luas.
Kelemahan (Weaknesses): posisi politik yang lemah, keterbatasan sumber daya material.
Peluang (Opportunities): akses pendidikan Barat, perubahan kebijakan kolonial, ruang diskusi di kota-kota besar.
Ancaman (Threats): dominasi kolonial, hegemoni ideologi Barat, represi politik.
Dari keempat unsur ini, tampak bahwa generasi Minang tidak menyerah pada kelemahan atau ancaman. Mereka justru memanfaatkan peluang untuk memperkuat diri, memupuk kesadaran nasional, dan mempersiapkan momentum kemerdekaan.
Warisan yang Terus Hidup
Warisan pemuda Minang masa kolonial bukan sekadar deretan nama pahlawan nasional. Lebih dari itu, mereka meninggalkan cara pandang strategis: mendengar tanpa larut, menyesuaikan tanpa kehilangan prinsip. Nilai ini amat relevan di era modern, ketika arus globalisasi membawa “kolonialisme baru” melalui kapitalisme, budaya pop, dan teknologi digital.
Kita boleh belajar dari luar, namun jati diri tetap menjadi jangkar. Dunia boleh berubah, tetapi filosofi Minang mengingatkan: “Dangakan nan diurang , laluan nan diawak.” Inilah pesan abadi yang membuat Minangkabau tak pernah kehilangan arah, bahkan di tengah pusaran sejarah paling genting sekalipun.
Sejarah Minangkabau di era kolonial adalah kisah tentang kecerdikan kultural bagaimana sebuah masyarakat kecil di pinggir barat Sumatera memanfaatkan peluang dari penguasa kolonial untuk merancang masa depan bangsanya sendiri. Bagi Belanda, pendidikan Barat mungkin alat penjinakan; tetapi bagi pemuda Minang, ia adalah batu loncatan menuju kebebasan.
Kecerdikan ini pula yang membuat Minangkabau tetap dikenang bukan karena mereka tunduk pada kekuasaan, tetapi karena mereka berdialog dengan zaman mengambil yang berguna, meninggalkan yang sia-sia, dan merumuskan arah bangsa dengan cara mereka sendiri.
Padang, Agustus 2025.
-------------------------------
Tentang Penulis*Muhammad Ishak, aktif di kegiatan Silat, baca Puisi dan Teater sejak belia sampai remaja, aktif dalam pementasan Teater dan Baca Puisi sejak tahun 1989 sampai dengan 1995 , tampil di Taman Ismail Marzuki Jakarta, dalam kelompok Teater Dayung Dayung pimpinan A.Alinde (alm) thn 1992 dan juga tampil di Taman Ismail Marzuki Jakarta (TIM) dengan Bumi Teater Pimpinan Wisran Hadi (alm) tahun 1994 ,dan aktif pementasan teater di Taman Budaya SUMBAR dan kota lainnya, ikut dalam forum Pejuang Seniman Sumatera Barat (FPS-SB) , serta terlibat sebagai pembicara dalam Kelompok Kreator Era AI, Satu Pena SUMBAR. Anggota Komunitas Pondok Puisi Inspirasi Pemikiran Masyarakat (PPIPM-Indonesia). Ia bekerja di dunia perbankan selama lebih kurang 28 tahun sejak tahun 1996 sebagian dihabiskan menjadi Direktur Utama selama 20 tahun di beberapa Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Sumbar dan mendirikan BPR milik Pemda Padang Pariaman pada thn 2007, sekarang sebagai Komisaris disamping Advokat dan aktif dalam kegiatan Kebudayaan dan Kesenian.
Pendidikan:
Ishak mengenyam pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Bung Hatta dan Magister Hukum pada Universitas Andalas.Hingga kini, Muhammad Ishak, aktif di kegiatan Silat, baca Puisi dan Teater sejak belia sampai remaja, aktif dalam pementasan Teater dan Baca Puisi sejak tahun 1989.
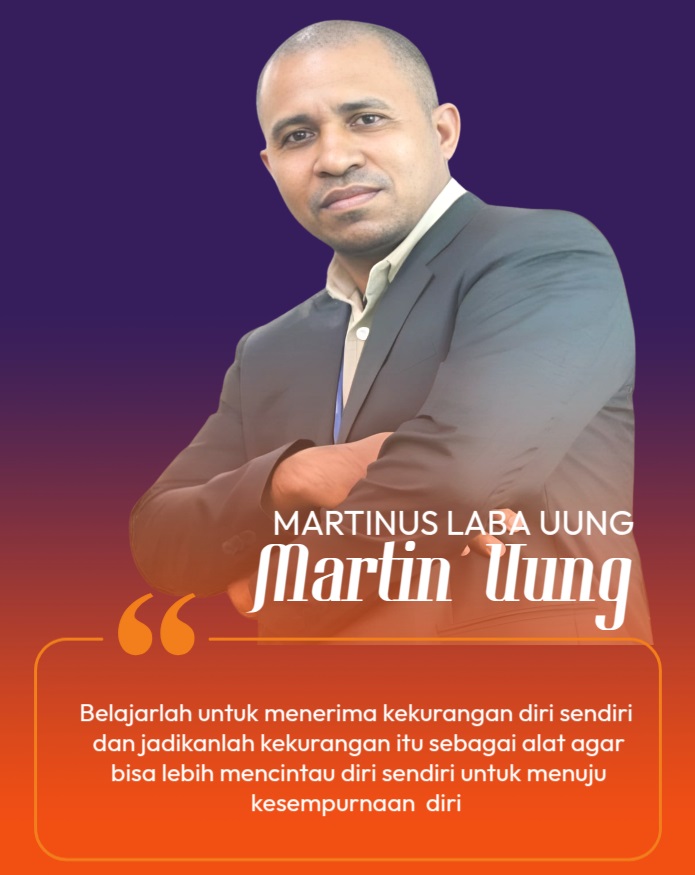

2.65K
141